Oleh: Ilmi Girindra
Imajinari.com - Kadang saya mikir, seandainya Doraemon beneran ada di dunia nyata, mungkin dia sekarang udah capek bantuin kita. Lelah. Muak. Mungkin udah pulang lagi ke abad ke-22 dan membuang kantong ajaibnya ke TPA Bantar Gebang.
Karena jujur saja—kita ini seperti Nobita. Banget. Bahkan lebih parah. Nobita paling-paling cuma minta alat buat nyontek PR, menghindari Giant, atau jalan bareng Shizuka. Sementara kita? Minta diselamatkan dari kemiskinan, korupsi, krisis pangan, resesi moral, bahkan dari kebodohan kolektif. Semua itu kita harapkan bisa selesai… asal ada “alat ajaib”.
Dan siapa Doraemon kita?
Pemerintah? Pemimpin baru? Influencer? Proyek strategis nasional? AI? Tuhan?
Entahlah. Yang jelas, kita lebih suka berharap ada yang datang dari laci meja dan membereskan semuanya. Padahal laci kita isinya cuma bon utang, berkas tilang, dan surat undangan nikah mantan.
Kantong Ajaib dan Mental Instan
Saya ingat waktu kecil, nonton Doraemon bikin saya percaya bahwa hidup itu bisa gampang. Mau terbang? Tinggal pakai Baling-Baling Bambu. Mau tahu masa depan? Ada Mesin Waktu. Mau populer? Ada Stiker Pengubah Nasib.
Lalu saya tumbuh. Dan sadar bahwa di Indonesia, kita masih percaya yang begituan.
Bukan baling-baling bambu, tapi janji-janji kampanye. Bukan mesin waktu, tapi proyek nostalgia masa lalu. Bukan stiker ajaib, tapi pencitraan murahan. Kita menuntut perubahan, tapi ogah berubah. Kita teriak soal keadilan, tapi senang main aman. Kita benci korupsi, tapi kalau ada “amplop bensin”, kita pura-pura lupa idealisme.
Mirip Nobita, yang tahu salah tapi tetap melakukannya, karena toh nanti Doraemon bisa memperbaiki.
Doraemon Tak Akan Selamanya Ada
Dalam salah satu episode paling menyayat, Doraemon mati (atau rusak berat), dan Nobita harus hidup tanpanya. Dia nangis, stres, jatuh... lalu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nobita berdiri. Dia belajar bela diri. Dia belajar matematika. Dia belajar hidup.
Dan saya ngeri membayangkan: kalau Doraemon benar-benar tak pernah kembali, apakah kita juga akan belajar? Atau justru semakin tenggelam, menuduh laci meja tak adil, menyalahkan semua hal kecuali diri sendiri?
Nobita adalah Cermin Kita
Kadang saya lihat berita dan merasa kita ini seperti karakter dalam anime itu. Ada Shizuka—simbol masa depan cerah yang terus dipuja tapi tak pernah digapai. Ada Giant dan Suneo—yang berkuasa dan kaya sejak kecil, suka main keroyokan, lalu bilang “semua demi rakyat”.
Dan kita? Tetap Nobita.
Mudah menangis. Sering marah. Sering menyalahkan. Sering lupa bahwa alat-alat ajaib tak akan berguna kalau kita tetap jadi pribadi yang sama: malas, manja, dan lari dari kenyataan.
Akhir Kata dari Laci Meja Saya
Andai saya punya satu alat Doraemon hari ini, saya tak mau Mie Instan Berubah Jadi Uang Tunai. Saya cuma mau Cermin Penerang Diri. Biar kita bisa melihat siapa sebenarnya biang kerok kekacauan ini. Biar kita sadar bahwa Doraemon sudah cukup memberi contoh.
Sekarang giliran kita jadi manusia. Bukan robot.
Bukan tokoh fiksi. Bukan Nobita.
Tapi kita—manusia Indonesia yang harusnya bisa lebih dari sekadar mengeluh di depan TV sambil berharap alat ajaib datang dari langit.
Tapi... ya, siapa tahu minggu depan Doraemon muncul beneran di Istana. Kan negeri ini apa pun bisa terjadi. Bahkan keajaiban paling absurd pun.
Ya, asal bukan kerja keras. Soalnya itu... terlalu fiksi untuk kita.
Kita, Si Pecandu Laci
Baik. Saya lanjutkan.
Yang menyedihkan dari semua ini bukan karena kita seperti Nobita. Tapi karena kita tahu kita seperti Nobita, dan kita bangga dengan itu.
Lihat saja setiap kali ada “bantuan”. Antri berdesakan, teriak-teriak, bahkan saling dorong. Bukan karena lapar semata, tapi karena sudah terbiasa hidup dalam ketergantungan.
Kita bahkan mulai memuja mereka yang bisa membuka “laci bantuan” lebih cepat, lebih besar, lebih sering—meskipun itu hasil dari manipulasi, pencitraan, atau bahkan manipulasi data.
Saya sering bertanya ke diri sendiri:
Kapan terakhir kali kita sebagai bangsa benar-benar bekerja keras, berpeluh, dan bangga karena hasil keringat sendiri—bukan karena diberi?
Dan yang lebih menakutkan:
Kapan terakhir kali kita diajarkan untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan jujur—tanpa harus disuapi dari kantong ajaib berbentuk subsidi, bansos, dan pencitraan spiritual di media sosial?
Doraemon Adalah Sistem
Dan Kita yang Memanfaatkannya
Sebenarnya Doraemon tak salah. Ia hanya simbol. Filosofi dari sistem yang dirancang untuk membantu, bukan memanjakan. Tapi kita—dalam sistem demokrasi setengah hati, kapitalisme penuh utang, dan budaya instant gratification—telah menyulap Doraemon menjadi pelayan pribadi, bukan partner belajar.
Alih-alih berkembang, kita malah tumbuh besar tanpa bertumbuh dewasa.
Mungkin inilah mengapa walau negara ini sudah 79 tahun merdeka, kita tetap sibuk mempersoalkan hal yang itu-itu saja: harga beras, BBM, pendidikan yang mahal, dan siapa yang bakal kasih “alat” paling menggiurkan di pemilu.
Episode Terakhir?
Seandainya hidup kita ini anime, saya takut ending-nya bukan Nobita jadi dewasa, tapi lacinya jebol karena terlalu sering dibuka. Kantong ajaibnya sobek, dan kita mulai sadar:
“Kita sudah tua, tapi belum bisa jalan sendiri.”
Tapi belum terlambat.
Kita masih bisa memilih berhenti menjadi Nobita. Kita masih bisa mulai membuka kantong ajaib kita sendiri—bukan dari teknologi masa depan, tapi dari nilai-nilai masa lalu: kerja keras, jujur, gotong royong, dan keberanian untuk berkata, “Saya salah. Saya mau belajar.”
Catatan Kaki dari Seorang Nobita yang Sedang Belajar Dewasa
Saya menulis ini bukan karena merasa lebih baik. Saya juga tumbuh di era yang sama, sering berharap sesuatu datang dari luar untuk menyelamatkan. Tapi makin ke sini, saya sadar: Doraemon tak akan datang.
Dan justru karena itu, kita semua harus menjadi sedikit lebih Doraemon bagi sesama—bukan dengan alat ajaib, tapi dengan waktu, pikiran, dan keberanian untuk berkata jujur dalam dunia yang penuh kepalsuan.
Karena mungkin, satu-satunya alat ajaib yang benar-benar kita punya adalah kesadaran.
Dan saya harap, laci itu kini mulai terbuka dari dalam kepala kita. Bukan dari meja. Bukan dari janji. Tapi dari niat.
Kalau tidak... ya sudah. Mungkin kita memang hanya bangsa figuran dalam anime tak berkesudahan: “Nobita dan Negeri yang Tak Pernah Belajar.”
Tamat?
Atau baru mulai?. (*)
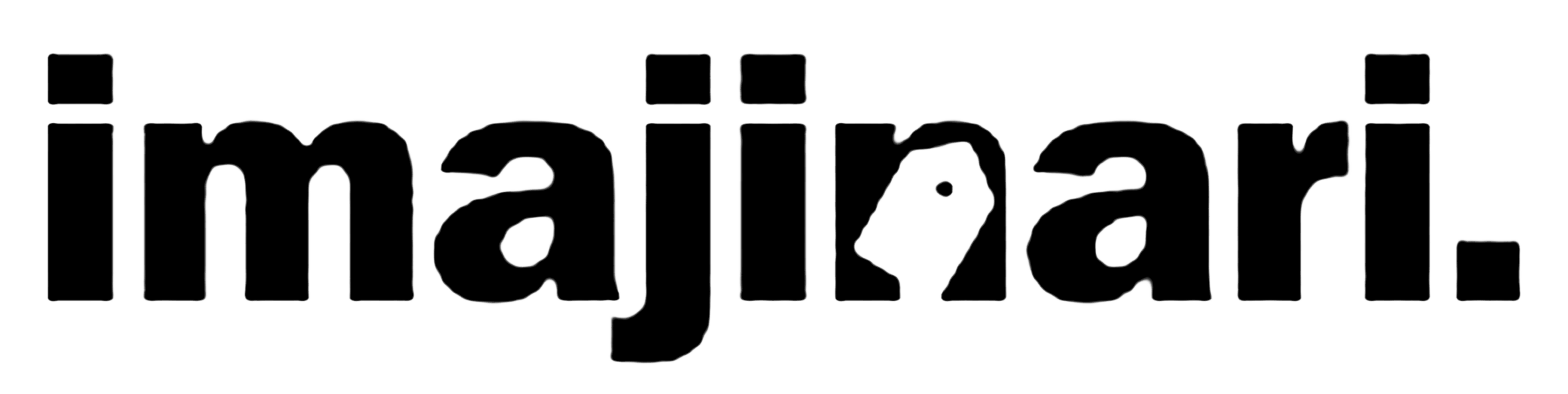
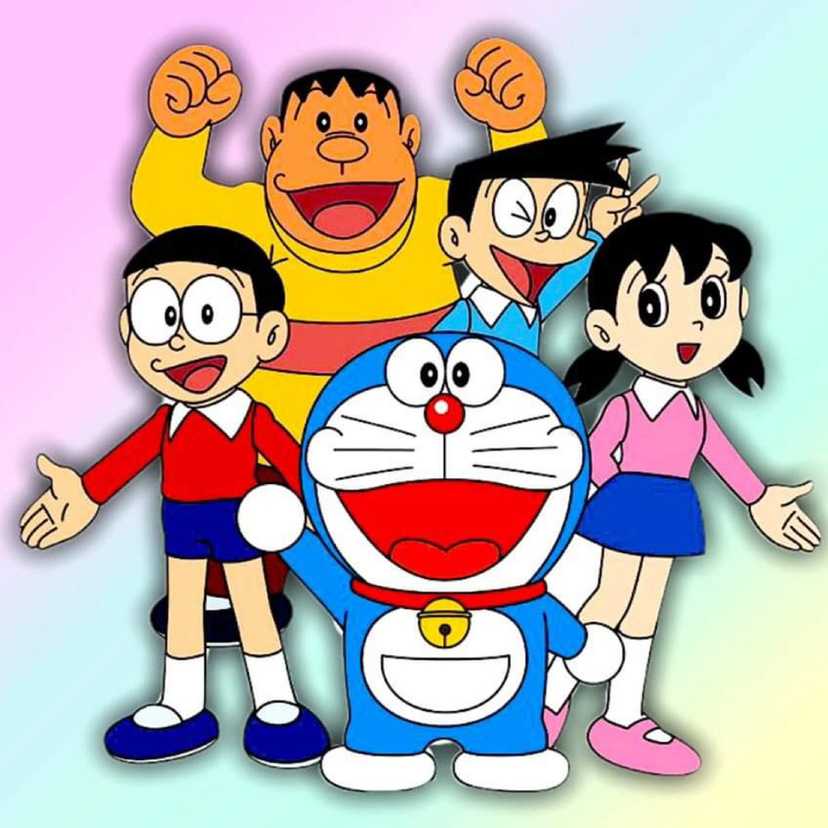

0 Komentar :
Belum ada komentar.