Oleh: Ilmi Girindra
Imajinari.com - Saya tidak sedang menulis biografi.
Ini bukan cerita tentang seseorang yang luar biasa. Bukan juga kisah penuh heroisme. Ini hanyalah catatan dari seseorang yang mencoba — mencoba memahami hidup, menempuh jalan, jatuh, bangun, dan terus bertanya: “Untuk apa semua ini?”
Saya tidak ingin dipuja. Bahkan tidak berharap untuk diingat. Tapi jika ada satu dua hal dari cerita ini yang bisa jadi cermin, jadi peringatan, atau bahkan sekadar peneguh bagi mereka yang sedang lelah, maka saya anggap semua ini layak dituliskan.
Jejak Langkah dari Kampung
Saya lahir di Bandung, besar di Garut. Tumbuh di antara nilai-nilai yang keras namun jujur. Belajar dari almarhum ayah saya, bahwa prinsip adalah hal terakhir yang boleh dijual. Dan dari kehidupan itu sendiri, saya belajar bahwa tidak semua orang mendapat panggung — tapi setiap orang bisa memilih untuk tetap berdiri.
Saya pernah jadi demonstran. Pernah jadi sales buku. Jadi jurnalis. Lalu bankir. Sampai akhirnya memutuskan untuk membangun jalan sendiri: mendirikan perusahaan, membangun akademi olahraga, menghidupkan media, dan menginisiasi koperasi berbasis gotong royong.
Saya menulis semua ini bukan untuk menceritakan apa yang telah saya capai — melainkan apa yang saya perjuangkan.
Karena pada akhirnya, bukan nama yang ingin saya tinggalkan. Tapi nilai.
Dan jika hidup ini hanya sebentar, semoga setiap detiknya bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri saya sendiri.
Prinsip di Tengah Kegamangan
Saya lahir di Bandung, tapi Garutlah yang membesarkan saya — bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin dan cara pandang. Garut bukan kota besar. Tapi bagi saya, di sanalah dunia saya terbentuk: cara berpikir, cara bertahan, dan cara menghargai kehidupan.
Di kampung tempat saya tumbuh, hidup tidak dibangun dari ambisi besar. Ia dibangun dari kerja keras, dari pengorbanan diam-diam orang tua, dan dari nilai-nilai sederhana yang diwariskan turun-temurun.
Di sanalah saya belajar mendengar sebelum berbicara, mengamati sebelum menilai, dan bersyukur meski dalam keterbatasan.
Sosok paling berpengaruh dalam masa kecil saya adalah almarhum Bapak saya, Mamat Rachmat. Beliau bukan tokoh publik, bukan pemilik panggung besar.
Tapi dari beliau saya belajar satu hal yang selalu saya bawa hingga hari ini:
"Pegang prinsip, selama itu benar dan ditujukan untuk kemanusiaan."
Itu bukan slogan. Itu cara hidup beliau. Dan itulah yang perlahan masuk dalam darah saya, bahkan ketika saya belum sepenuhnya sadar.
Kami bukan keluarga kaya. Tapi kami cukup. Cukup cinta, cukup nilai, cukup alasan untuk tidak iri pada yang lebih punya. Dari sana saya belajar bahwa harga diri tidak datang dari gelar atau jabatan, tapi dari kejujuran dan keteguhan hati.
Saya masih ingat betul suasana malam Garut — sunyi, dingin, dan penuh ruang untuk merenung. Di situlah saya tumbuh sebagai pengamat. Tidak banyak bicara, tapi menyimpan banyak tanya. Tentang hidup, tentang ketidakadilan, tentang mimpi yang rasanya terlalu jauh dari kampung kecil kami.
Saya tahu sejak awal, saya tidak dilahirkan untuk hidup nyaman. Tapi saya percaya, saya bisa hidup bermakna.
Bukan untuk jadi pahlawan. Tapi untuk tetap manusia. Tetap waras. Tetap jujur. Tetap percaya bahwa nilai-nilai yang diajarkan Bapak saya tidak akan pernah ketinggalan zaman.
Dan dari Garut — kota kecil yang membesarkan saya — saya melangkah. Tidak dengan segala jawaban, tapi dengan tekad untuk terus mencari.
Kadang salah arah. Kadang jatuh. Tapi tidak berhenti. Karena suara Bapak selalu ada di hati saya: "Teruslah berjalan, Nak. Dunia butuh lebih banyak orang yang jujur dan teguh. Hidup bukan soal menang atau kalah. Tapi soal tetap berdiri di pihak yang benar."
Belajar Menjadi Manusia
Saya mulai menyadari, dunia tidak sesederhana kampung tempat saya tumbuh. Di luar sana, hidup punya logikanya sendiri.
Ada yang menang karena jujur, tapi lebih banyak yang menang karena licik. Ada yang dihargai karena kerja keras, tapi lebih banyak yang dipuja karena popularitas kosong.
Di titik itu, saya mulai bertanya: apa sebenarnya arti menjadi manusia?
Sekolah memberi saya ijazah. Tapi kehidupan yang benar-benar mendidik. Saya belajar dari kegagalan, dari ditolak, dari diabaikan, dari kesepian, dari dikhianati.
Bukan dari teori, tapi dari luka. Saya belajar bahwa menjadi manusia itu lebih sulit daripada sekadar hidup.
Saya tidak pernah merasa jadi orang baik. Bahkan sampai hari ini. Tapi saya selalu mencoba menjadi orang yang terus belajar.
Belajar dari siapa saja: dari teman, dari lawan, dari anak-anak, dari orang yang tidak saya suka, bahkan dari makhluk dan alam. Saya percaya, setiap peristiwa adalah guru — asal kita mau merunduk untuk mendengarkan.
Ada masa-masa di mana saya merasa sendirian. Saat saya tetap bertahan pada prinsip, dan yang saya dapat justru cibiran.
Tapi saya ingat betul pesan Bapak: "Kalau kamu berdiri untuk yang benar, jangan berharap ramai. Kadang kamu harus siap berjalan sendirian."
Itu berat. Tapi itu membuat saya tahan. Membuat saya berhenti mencari pengakuan, dan mulai mencari dampak.
Dari sanalah saya mulai berpikir, idealisme tidak cukup hanya menjadi gagasan. Ia harus diberi bentuk. Harus diperjuangkan.
Harus ditanamkan dalam sistem, komunitas, bahkan organisasi. Saya tidak ingin hanya marah pada keadaan. Saya ingin mengubahnya — semampu yang saya bisa.
Saya mulai menulis, mengorganisir, membuat gerakan kecil, mendirikan akademi, membangun gagasan tentang koperasi olahraga, menyuarakan hak komunitas, dan berdiri untuk hal-hal yang dianggap sepele oleh banyak orang. Bukan karena saya lebih tahu, tapi karena saya tidak tahan diam.
Semakin banyak saya belajar, semakin saya sadar bahwa menjadi manusia tidak butuh kesempurnaan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk tetap berpihak, bahkan ketika keadaan tidak berpihak pada kita.
Menjadi manusia, bagi saya, adalah proses panjang. Bukan untuk menjadi lebih tinggi dari orang lain.
Tapi justru untuk menjadi lebih membumi — memahami luka orang lain, menghargai perjuangan kecil, dan terus merawat harapan.
Sampai hari ini, saya masih belajar. Dan mungkin, seumur hidup saya memang ditakdirkan untuk itu: belajar menjadi manusia.
Prinsip di Tengah Kegamangan
Tidak semua yang benar akan dimenangkan. Tidak semua yang salah akan ditinggalkan.
Saya kira hidup akan memihak pada logika itu. Tapi hidup, ternyata, punya wajahnya sendiri.
Dan di wajah itu, saya berkali-kali ditantang: Masihkah kamu mau bertahan dengan prinsip, ketika dunia menyodorkan jalan pintas?
Saya sempat goyah. Siapa yang tidak?
Ketika pekerjaan menuntut kompromi. Ketika lingkungan menekan untuk diam.
Ketika orang yang dulu bersamamu mulai berubah arah demi keuntungan sendiri.
Saya sempat bertanya dalam hati: apakah saya sedang keras kepala, atau sedang setia?
Karena kadang, setia pada nilai justru membuatmu terlihat seperti pecundang di mata banyak orang. Seolah kamu bodoh karena tidak mau ikut arus.
Padahal saya tahu, saya bukan suci. Saya bukan pahlawan. Saya juga butuh makan. Butuh pengakuan. Butuh rasa aman.
Tapi tetap saja, ada suara di dalam diri saya yang tidak bisa saya bunuh:
"Kalau kamu menyerah sekarang, kamu kehilangan alasan kenapa kamu berangkat dari awal."
Dan di tengah semua kegamangan itu, saya mulai menyadari satu hal: Prinsip itu bukan hanya soal apa yang kita pegang, tapi siapa kita tanpa prinsip itu.
Kalau saya lepaskan prinsip itu, saya bukan siapa-siapa lagi. Saya hanya angka, hanya nama, hanya bagian dari statistik manusia yang hidup tanpa arah.
Maka saya memilih tetap memegangnya. Meski sulit. Meski sunyi. Meski kadang harus pura-pura kuat di depan orang lain.
Saya memilih untuk tetap berjalan, sambil membawa luka dan harapan sekaligus. Karena saya percaya: kemenangan sejati bukan soal siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang tidak menyerah saat digoda untuk berhenti.
Saya belajar bahwa kadang perjuanganmu tidak akan dilihat. Tidak akan dihargai. Tidak akan dianggap penting oleh sistem yang korup dan masyarakat yang letih.
Tapi saya juga belajar bahwa diam itu mematikan. Dan satu-satunya cara untuk tetap hidup dengan utuh adalah tetap menyuarakan kebenaran — walau hanya satu dua orang yang mendengarnya.
Saya hidup dalam dunia yang sering kali abu-abu. Tapi saya tetap berusaha menata arah kompas saya:
Bukan ke popularitas. Bukan ke uang. Tapi ke nilai.
Nilai yang dulu diajarkan bapak saya. Nilai yang membuat saya tetap bisa tidur tenang, meski dunia berkata saya kalah.
Dan dari situlah saya mengerti:
memegang prinsip di tengah kegamangan bukan kelemahan. Itu keberanian.
Prinsip di Tengah Kegamangan
Saya tidak lahir dari garis keturunan elit. Tidak juga dibekali koneksi istimewa. Tapi saya punya satu hal yang selalu saya rawat: keyakinan bahwa manusia bisa mengubah takdirnya dengan niat yang jernih dan langkah yang jujur.
Masa muda saya bukan hanya diisi oleh sekolah dan buku. Ada gelora yang lebih besar dari itu. Di penghujung Orde Baru, saya ikut menyaksikan — bahkan terlibat — dalam gelombang perubahan.
Tahun 1997–1998, saya turun ke jalan.
Menjadi bagian dari arus demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menuntut reformasi. Suara klakson, asap ban terbakar, dan pekik orasi bukan sekadar simbol perlawanan.
Itu sekolah kehidupan saya yang sebenarnya. Saya belajar bahwa perubahan tidak datang dari diam, tapi dari keberanian untuk bersuara.
Bahkan setelah lulus SMA tahun 1998 — sebagai lulusan terbaik ketiga dari SMA 1 Garut (sekarang SMA 11 Garut) — saya masih tetap membantu kawan-kawan yang mengorganisir gerakan hingga tahun 2005.
Bagi saya, memajukan manusia dan kemanusiaan bukan tren. Itu panggilan.
Di saat yang sama, saya sadar bahwa idealisme harus bersanding dengan kemampuan untuk hidup mandiri. Maka saya mulai dari nol. Betul-betul dari nol.
Saya pernah menjadi sales buku yang mendorong troli berisi buku-buku kecil di Bandung.
Saya jalani itu dengan kepala tegak. Karena saya percaya, pekerjaan tidak pernah merendahkan martabat. Yang merendahkan manusia adalah ketika ia berhenti berusaha.
Dari sana, saya berpindah ke dunia jurnalistik. Saya bekerja di beberapa media cetak di Jawa Barat dan Jawa Timur, kemudian juga di beberapa stasiun TV nasional sebagai reporter. Saya menulis, meliput, dan menjadi saksi berbagai peristiwa.
Menjadi jurnalis mengasah kepekaan saya terhadap realitas, dan mengajarkan saya untuk terus dekat dengan denyut rakyat.
Setelah itu, saya menyeberang ke dunia yang sangat berbeda: perbankan.
Berbagai jabatan strategis pernah saya emban dibidang ini.
Saya tidak sampai ke sana karena koneksi. Saya sampai karena kerja keras dan kesediaan untuk terus belajar.
Namun pada akhirnya, saya tahu: hidup yang saya cari bukan tentang jabatan.
Di akhir 2019, saya mengundurkan diri. Saya ingin membangun sesuatu yang betul-betul saya yakini.
Tahun 2020, di tengah pandemi, saya mulai merintis perusahaan sendiri.
Sebelumnya, tahun 2015, saya sudah pernah mencoba membuka usaha kedai kopi.
Bisnis kecil, tapi besar harapannya. Saya ingin menjadikan tempat itu bukan sekadar tempat minum kopi, tapi juga tempat berkumpulnya ide, tempat bertemunya rasa dan logika.
Saya juga ikut menginisiasi komunitas Sabanda Sariksa — wadah yang menghidupkan kembali nilai-nilai sosialisme karuhun Sunda.
Bagi kami, gotong royong bukan jargon. Ia adalah sistem nilai yang harus dihidupkan lagi di tengah zaman yang makin individualistik.
Kami percaya: kearifan lokal bukan barang kuno. Ia bisa menjadi jalan modern yang lebih manusiawi.
Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya ingin membangun yang tidak ada — bukan untuk dikenang, tapi untuk diwariskan.
Bukan untuk dipuja, tapi untuk dirasakan dampaknya oleh mereka yang mungkin tidak pernah tahu nama saya.
Merekam, Merawat, Melawan
Antara Media, Akademi, dan Gerakan
Jika ada satu hal yang terus saya bawa sejak muda, itu adalah keresahan. Tapi saya tidak mau berhenti di resah. Karena resah yang tidak berubah jadi gerak, hanya akan jadi beban batin.
Maka saya menulis, merekam, membangun, dan mengorganisir. Bukan karena merasa lebih tahu, tapi karena saya ingin menjadi bagian dari solusi.
Saya menyadari, ruang-ruang informasi kita sudah terlalu lama dikuasai segelintir suara.
Yang minor, yang marjinal, yang alternatif — sering kali hanya jadi catatan kaki. Maka saya membangun jalur sendiri.
Bersama beberapa kawan, kami dirikan PT. Beranda Media Alternatif (BMA), dan mengelola sembilan media daring, masing-masing punya warna dan keberpihakan yang jelas.
Dari akademiaagarut.com yang fokus pada pendidikan dan olahraga lokal, sampai pantaupolitik.com yang kritis terhadap arah kebijakan.
Dari matakanan.com yang merawat kuliner sebagai identitas budaya, sampai daspublika.com yang memberi ruang pada suara rakyat.
Saya percaya, media bukan hanya bisnis. Ia alat perjuangan. Ia bisa merekam ingatan, membongkar kepalsuan, dan merawat harapan.
BMA bukan perusahaan besar. Tapi saya ingin ia tumbuh dengan idealisme yang tak bisa dibeli.
Namun saya tahu, perlawanan tidak bisa hanya lewat tulisan. Harus juga ada yang bekerja di lapangan. Maka saya dirikan sesuatu yang bahkan lebih dekat dengan tanah: Akademi & Klub Bola Voli AA Garut.
Bukan sekadar tempat latihan. Bukan sekadar tim tanding. Akademi ini lahir dari keresahan: mengapa anak-anak daerah tidak punya sistem pembinaan yang jelas? Mengapa bakat-bakat muda harus dikorbankan hanya karena kurang fasilitas atau jaringan?
Kami membangun sistem pelatihan profesional, menyusun SOP pelatih, merancang model transfer dan peminjaman pemain, bahkan menyisipkan program pembentukan karakter, akhlak, dan soft skills.
Kami ingin menjadikan olahraga sebagai jalan pembebasan sosial.
Dari akademi itu pula lahir satu gagasan gila: Koperasi Olahraga. Kami melihat, atlet tidak hanya butuh panggung. Mereka butuh sistem ekonomi yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
Maka kami rancang model koperasi yang mengelola bukan hanya olahraga, tapi juga pendidikan, pelatihan bahasa, usaha kecil, hingga pemodalan komunitas.
Semuanya dimulai dari Garut. Tapi impiannya nasional.
Saya tahu ini jalan terjal. Banyak yang mencibir, banyak yang meremehkan. Tapi saya percaya, melawan itu bukan selalu teriak di jalanan. Kadang melawan berarti merawat, mendidik, membangun — dan tetap jujur pada nilai yang kita yakini.
Di usia sekarang, saya mungkin tidak bisa lagi turun ke jalan. Tapi saya bisa membangun panggung sendiri. Saya bisa menulis.
Saya bisa membuka jalan untuk anak-anak muda, agar mereka tidak harus kehilangan masa depan hanya karena sistem yang timpang.
Bagi saya, perlawanan itu bukan kemarahan. Tapi cinta. Cinta pada negeri ini. Cinta pada manusia.
Dan cinta pada kemungkinan bahwa sesuatu yang lebih adil masih bisa diperjuangkan — asal kita tidak menyerah.
Apa yang Ingin Saya Wariskan?
Saya tidak sedang mencari abadi. Saya tidak bercita-cita menjadi legenda.
Tapi saya ingin, ketika saya selesai nanti, ada sesuatu yang tetap tinggal — bukan nama saya, tapi nilai-nilai yang pernah saya perjuangkan.
Saya ingin mewariskan keberanian untuk berpikir berbeda.
Untuk tidak hanya menjadi bagian dari kerumunan, tapi juga menjadi penyala di tengah kegelapan.
Saya ingin anak-anak muda tahu, bahwa mereka tidak harus jadi siapa-siapa untuk memulai sesuatu. Cukup jadi diri sendiri, tapi yang jujur. Yang gigih. Yang punya tujuan.
Saya ingin warisan saya bukan gedung atau aset, tapi semangat.
Semangat untuk membangun dari bawah. Untuk bergerak tanpa menunggu komando. Untuk tidak menjilat kekuasaan demi kelangsungan pribadi.
Saya ingin, ketika orang-orang menyebut nama saya kelak, mereka tidak bicara soal posisi atau pencapaian. Tapi soal nilai:
"Orang ini pernah berjuang, meski tahu hasilnya mungkin tidak akan sempat ia nikmati sendiri."
Saya ingin mewariskan ruang. Ruang tempat orang berpikir dan bertindak bebas — dengan tanggung jawab dan kesadaran.
Ruang bagi siapa saja yang ingin belajar tanpa dihina. Bagi siapa pun yang ingin mencoba, tanpa harus merasa sendiri.
Saya ingin, suatu hari nanti, jika anak saya atau siapa pun membaca jejak langkah saya, mereka bisa berkata:
"Ayah (atau orang ini) bukan orang yang sempurna. Tapi ia tidak berhenti mencoba menjadi lebih baik. Ia tidak pernah lupa pada yang lemah. Dan ia tidak pernah menjual nilai yang ia yakini."
Saya ingin, di tengah dunia yang makin gaduh dan cepat, ada yang tetap percaya pada yang pelan, tekun, dan jujur.
Saya ingin keyakinan saya tidak ikut terkubur saat saya tiada.
Saya ingin, meski kecil, saya pernah menjadi bagian dari cerita tentang manusia yang tak menyerah pada kemanusiaannya.
Dan jika saya boleh memilih bagaimana dikenang, saya ingin dikenang bukan karena apa yang saya miliki, tapi karena apa yang saya tanam — dan biarkan tumbuh, meski mungkin saya tak sempat memetiknya.
Tentang Jalan yang Dipilih
Setiap orang berjalan di jalan yang berbeda. Ada yang memilih jalan terang, penuh tepuk tangan dan sorot lampu.
Ada juga yang memilih jalan sunyi, dipenuhi pertanyaan dan keraguan. Saya mungkin lebih dekat pada yang kedua.
Tapi saya tidak menyesal. Karena dari sunyi itulah saya bisa mendengar suara hati saya sendiri.
Dari sunyi itu saya bisa melihat lebih jernih: siapa kawan sejati, siapa yang hanya datang saat pesta.
Dari jalan itulah saya belajar bahwa kemuliaan tidak selalu hadir dalam kemewahan.
Kadang ia bersembunyi di balik kesederhanaan, dalam kerja diam-diam, dalam keringat yang tidak ditayangkan.
Saya tidak mengklaim jalan ini benar untuk semua orang. Tapi ini jalan yang saya pilih. Dengan sadar. Dengan seluruh luka dan cinta yang menyertainya.
Saya tahu saya bukan orang baik. Bukan juga orang yang paripurna. Tapi saya terus berusaha.
Saya belajar dari siapa pun. Dari mereka yang pernah menyakiti saya, juga dari mereka yang diam-diam mendoakan saya.
Saya belajar dari setiap anak yang tersenyum di tengah kekurangan, dari setiap petani yang menanam meski hujan tak kunjung turun, dari alam yang tak pernah menuntut, tapi selalu memberi.
Saya lahir di Bandung, tumbuh di Garut. Di kota ini saya jatuh, dan bangkit berkali-kali.
Di kota ini pula saya belajar mencintai Indonesia — bukan sebagai slogan, tapi sebagai medan juang.
Dan kelak, jika saya tak lagi ada, saya hanya berharap satu hal:
Semoga ada satu-dua orang yang meneruskan apa yang saya mulai. Bukan dengan cara yang sama, tapi dengan semangat yang serupa.
Semoga, walau kecil, jejak ini bisa jadi arah bagi mereka yang tengah mencari jalannya.
Semoga nilai-nilai yang saya genggam tidak ikut hilang bersama tubuh saya, tapi terus mengalir — dari satu hati ke hati lainnya.
Sebab hidup, pada akhirnya, bukan soal berapa lama kita tinggal di dunia.
Tapi berapa banyak kebaikan yang tetap tinggal, bahkan setelah kita tiada. (*)
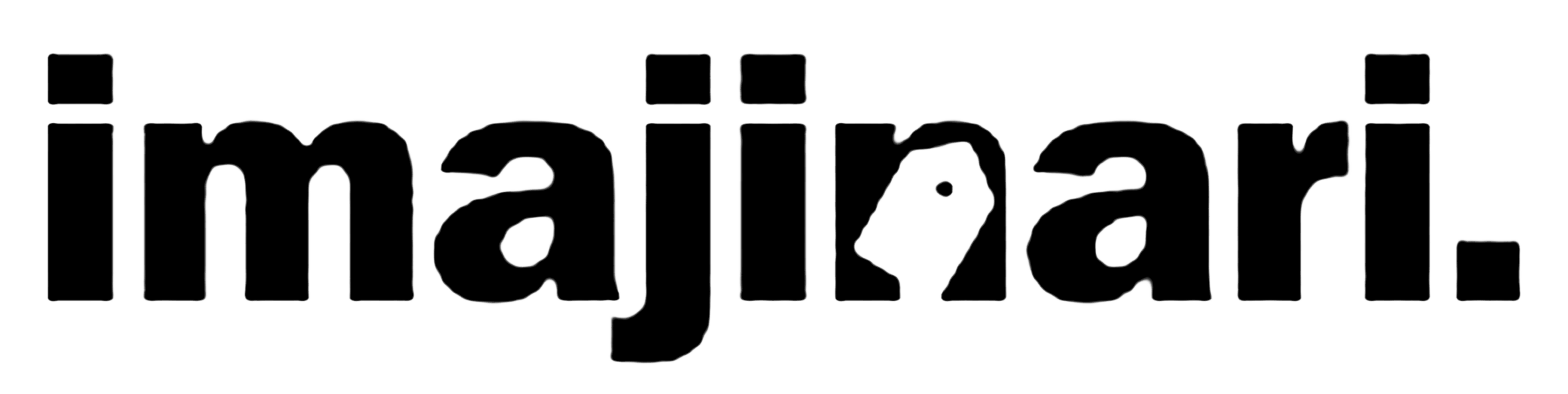


0 Komentar :
Belum ada komentar.